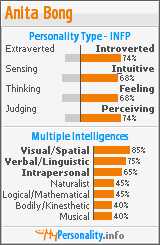Media menatap tajam Dewan Parlemen di hadapannya. Kedua tangannya dia letakkan diatas berkas-berkas yang berserakan. Dia baru saja mengakhiri argumennya, kini dia hanya perlu memastikan para tetua menandatangani draft perjanjian distribusi pangan. Dilihatnya satu per satu para tetua dengan janggut putihnya, meyakinkan bahwa keputusan yang diambilnya ini akan dapat menyelamatkan negeri mereka dari kelaparan. Sementara suara teriakan rakyat menjadi musik latar dari ruang rapat yang diisi oleh selusin tetua.
Di luar sana, terjadi unjuk rasa besar-besaran di depan gedung Parlemen bergaya klasik itu. Perang di dalam, kerusuhan di luar.
Salah satu tetua berdiri, Media mengenalnya sebagai Ariokh, salah satu yang paling berpengaruh di dewan. Ariokh berjalan menuju jendela dengan sebuah senyum tenang, memandangi keributan yang berjarak hanya lima puluh meter dari bangunan itu. Dari lantai dua dia dapat melihat betapa marahnya rakyat dibawah sana.
Dengan anggun dia mengelus jenggot putihnya, "Media, apa kau tahu kenapa mereka datang kemari?"
Media tidak menjawab, bukan karena dia tidak tahu. Dia menatap Ariokh dengan mengancam. Giginya gemeletuk di balik rahangnya, menahan emosi.
"Mereka menuntutmu untuk diadili karena dituduh telah menggelapkan uang negara." Lanjut Ariokh seraya membalas tatapan Media, sebuah seringai muncul di wajahnya. "Sementara kamu disini memperjuangkan hidup mereka. Ironis...."
Media menekan buku-buku jarinya di meja dengan keras hingga memutih. Dalam hati dia mengutuki Ariokh, dialah yang menjadikan Media kambing hitam dari kekacauan yang ditimbulkan olehnya dan kini Media harus memohon agar Ariokh bersedia menandatangani berkasnya agar memiliki kekuatan hukum. Negara apa ini?!
"Tidak ada gunanya kamu bersikeras, Media. Tinggalkan idealismemu dan kita dapat berbicara untuk menentukan banyak hal." Lanjut Ariokh. "Kita juga bisa sedikit mengubah draftmu, agar semua pihak senang...."
Mati-matian Media menahan dirinya untuk tidak menyeberangi ruangan dan menghajar tua bangka itu. Rasio memaksanya berpikir resiko yang harus ditanggung hanya untuk memuaskan emosinya.
"Hmm...." Ariokh melihat jam sakunya. "Sudah waktunya minum teh. Kita beristirahat lima belas menit sebelum kita melanjutkan rapat tidak berguna ini...."
"Tu-tunggu, draft ini harus segera ditandatangani! Ada ribuan jiwa yang bertarung dengan maut menunggu distribusi makanan...." Seru Media namun tidak ada yang peduli.
Para tetua mengekor dibelakang Ariokh keluar ruangan, meninggalkan Media yang tidak bisa berbuat apapun. Ketika pintu tertutup dan kesunyian turun, Media tidak sanggup lagi menahan kekesalannya. Dipukulnya meja kayu itu dengan keras, membuat buku-buku jarinya memar.
"Argh!!!" Seru wanita itu.
Dia menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya. Akalnya terus memperingatkan bahwa dia akan butuh tenaganya untuk menghadapi para tetua. Media menghempaskan tubuhnya pada punggung kursi sambil memijat kepalanya. Ah...kira-kira apa yang dilakukan oleh ibunya sekarang?
Tiba-tiba kehangatan turun di hati wanita berumur tiga puluh tahun itu. Dalam benaknya terbayang seorang wanita tua yang selalu menjadi tempatnya berkeluh kesah tentang karirnya di pemerintahan. Tangan penuh kerut yang senantiasa memeluknya ketika dia lelah. Media tersenyum lembut. Betapa dia kangen dengan rumah. Sudah lebih dari sebulan dia tidak sempat bertegur sapa dengan ibunya, bahkan lewat surat sekalipun. Keadaan negeri genting karena pasokan makanan yang ditahan beberapa aristokrat membuat kelaparan merajalela belum lagi kasus yang menimpa dirinya membuat seluruh pikiran tersita.
Pikirannya melayang ke puluhan tahun silam, dia ingat, ibunyalah yang menanamkan nasionalisme dalam jiwanya. Mengajarinya untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dengan semangat yang sama, wanita tua itu melepas putri satu-satunya memasuki politik yang kejam walaupun dia lebih suka bila Media bersamanya di masa senja.
"Ibu...bagaimana jika negara yang mengkhianati kita?" Gumam Media lelah.
Media terdiam sejenak lalu mengambil napas. Setelah para tetua menyetujui draft ini, dia akan pulang....
Terdengar pintu diketuk, dengan malas Media berdiri dan membuka pintu. Wajah asistennya muncul dengan panik.
"Ada apa?" Tanya Media, sebuah firasat buruk menggantung di benaknya.
"Nona Media, ibu anda kritis!" Seru Sang Asisten.
Media merasa napasnya sesak, limbung dan dunia serasa berputar lebih cepat. Dia segera mencari pegangan untuk menahan tubuhnya yang tiba-tiba lemas.
"Nona!" Seru Asistennya makin panik.
"Aku tidak apa-apa." Ucap Media lebih kepada dirinya sendiri sambil terus menenangkan diri. "Lanjutkan ceritamu."
"Kemarin malam beliau tidak sadarkan diri. Dokter sudah melakukan segala macam cara tapi beliau tetap tidak sadarkan diri. Kata mereka, beliau mungkin tidak akan bertahan lama...."
Seandainya diizinkan untuk pingsan, dia tentu sudah melakukannya namun Media mencengkram erat tangannya untuk membuatnya tetap sadar.
"Nona Media, lebih baik anda segera pulang dan menemani ibu anda." Saran Sang Asisten makin khawatir dengan keadaan atasannya.
Ingin sekali Media langsung lari keluar dari bangunan ini dan segera memecut kereta kuda menuju desa kelahirannya namun ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan....
"Aku tidak bisa...." Ucap Media pelan, air mata menggumpal di sudut matanya. "Jika draft ini tidak ditandatangani parlemen, akan ada puluhan ribu orang kelaparan akan mati...."
"Tapi, Nona.... Ibu anda...membutuhkan anda...."
Media menghapus air mata yang tak sempat jatuh. Satu tarikan napas panjang dan dia sudah mengambil keputusan. Dia memandang asistennya dengan tatapan yakin khas dirinya. Sebuah senyum tersungging diwajahnya.
"Boleh aku minta tolong?" Ucapnya dengan ketenangan yang luar biasa.
"Y-ya?"
"Gantikan aku menemani ibu. Katakan padanya, anaknya sedang memperjuangkan negara di atas semua kepentingan pribadinya." Ucap Media dengan tegas. "Katakan padanya, anaknya akan memastikan kelaparan ini berakhir, apapun caranya...."
Terdengar gumam teredam tanda para tetua sudah kembali. Media segera meminta asistennya pergi sementara dia merapikan dirinya. Begitu pintu terbuka, para tetua satu per satu berjalan memasuki ruang rapat. Media bertatapan dengan Ariokh. Tidak satupun kesedihan terpancar dari mata itu, hanya sebuah determinasi yang teguh.
"Kau masih berada disini rupanya...." Ucap Ariokh dengan seringainya. "Kita lihat bagaimana rapat ini berakhir...."
*
Media berdiri seorang diri menatap langit kelabu. Serpihan-serpihan salju turun menyapanya. Musim gugur baru saja berlalu dan udara sudah semakin dingin. Segenap alam sedang bersiap untuk tidur panjang. Dia menghembuskan napas, uap langsung menyembul di depan hidungnya. Dia kemudian berlutut dan meletakkan setangkai bunga di depan sebuah nisan, bertuliskan nama ibunya. Sampai akhir, Media tidak bisa menemani ibunya.
"Ibu, aku tidak menyangka harga sebuah idealisme begitu mahal...." Ucap Media, air matanya menggenang. "Dia bahkan merenggut detik-detik terakhirku untuk menemani ibu...."
Media mengelus nisan dingin itu. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Tidak akan ada lagi tangan yang menunggunya pulang, tidak akan ada lagi kehangatan yang memberinya kekuatan. Media menghapus air matanya.
"Dan bukan hanya itu, ibu. Dia juga merenggutku dari tanah kelahiranku...."
Media berdiri, dia menoleh, seorang kusir mengangkat topinya memberi hormat sambil berdiri di samping sebuah kereta kuda. Media kembali menatap makam ibunya.
"Aku berhasil membuat Ariokh dan para tetua menandatangi draft undang-undang tentang pengaturan distribusi pangan setelah aku berjanji meninggalkan negeri ini, sebagai kriminal yang tidak pernah sempat membersihkan namaku...." Media tersenyum sedih. "Ibu, bukan aku yang mengkhianati negeri ini, tapi negeri ini yang mengkhianatiku...."
Media terdiam. Meresapi waktu yang kini berjalan begitu lambat. Ketika sebuah lonceng dibunyikan oleh sang Kusir, Media tahu waktunya telah selesai. Dia harus pergi sekarang atau malam segera tiba.
"Oh, tenang saja, ibu. Negeri yang aku tuju menawariku sebuah posisi dimana aku bisa bekerja dengan baik. Tidak ada lagi orang-orang seperti Ariokh...." Media kembali tersenyum getir. "Aku pasti akan kembali, Ibu, ketika negara ini sudah siap menerimaku...."
Media memberi sebuah senyum hangat terakhir sebelum dia berbalik dan berjalan pergi....
END
________________________________________________________
Sangat terinspirasi dari kisah Sri Mulyani di SINI
Naah~ I hate politics, dan aku tidak sedang berusaha mem-blow up ibu yang satu itu :) heheheh~ cuma, rasanya agak miris lihat orang-orang yang mampu menolong Indonesia lebih diakui di luar negeri. Contoh yang lain: B.J Habibie.
Semoga cerita ini dapat menjadi sebuah kisah perenungan bagi kita semua :)